POLITIK IDENTITAS ISLAM DAN EMPAT PERANG ACEH
Politik identitas keacehan yang dikonsepsikan sebagai Islami selalu menjadi langgam dari setiap perjuangan yang dilakukan Orang Aceh.
Reproduksi tentang paham Aceh yang islami terlihat dalam empat perang yang dijalankan Aceh; perang Aceh-Belanda, perang dalam revolusi fisik kemerdekaan Indonesia di Aceh, perang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh dan perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Islam dan proses islamisasi yang sudah berusia sekitar 1300 tahun di tanah Aceh selalu menjadi instrumen ampuh untuk memobilisasi semangat juang rakyat Aceh dalam semua periode perang Aceh.
Hal ini didasarkan pada asumsi atas dasar Islam dan demi Islamlah identitas keacehan itu dibina, dibela dan dipertahankan. Jadi tanpa Islam, Aceh tidak ada dan tentu saja memudarnya Islam sekaligus juga memudarnya Aceh.
Islam sebagai pembentuk kesadaran identitas keacehan yang paling utama kemudian telah menjadi jati diri dan citra diri Orang Aceh sekaligus juga menjadi harga diri Orang Aceh telah direproduksi sebagai daya dorong dan energi sosial politik utama bagi setiap perjuangan dan perang Aceh.
Perspektif dan metode pembahasan tulisan ini dielaborasi dalam bentuk diskusi deduktif – induktif. Diskusi ini terutama didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang berbicara tentang empat perang yang pernah terjadi di Aceh yang di dalamnya telah berkelindan identitas keacehan yang paling azasi yaitu islam.
Data-data sosial dalam konteks kekinian yang telah diamati juga ditampilkan untuk menunjukkan gejala kontinuitas historis pembahasan. Proses ideologisasi dan sakralisasi perang telah dimulai sejak perang Aceh-Belanda pada 1873.
Perang tidak lagi hanya dimaknai sebagai membela negeri tetapi menjadi perilaku spiritual dan ibadah yang disucikan. Kematian justru menjadi tujuan perang sebab di sanalah ia akan mejadi syuhada Allah untuk mendapat kehidupan bahagia yang hakiki.
Berperang dalam makna ini kemudian menjadi hal yang membanggakan bagi kesadaran sebagai Orang Aceh. Semangat perang suci ini kemudian menjadi kenangan yang membanggakan dan terus direproduksi baik pada perang Aceh dalam membela kemerdekaan Indonesia, perang DI/TII Aceh dan perang GAM. Kata kunci: Islam, Politik Identitas, Perang Aceh.
A. Pendahuluan : Aceh dan Nilai-Nilai Islam
Islam adalah pembentuk kesadaran identitas keacehan1 uatama. Proses Islamisasi yang sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Islam Peureulak (sekarang berada dalam wilayah Aceh bagian timur) pada abad ke 8, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Islam Pase (sekarang berada dalam wilayah Aceh di bagian utara) sekitar abad ke 13 dan kemudian disusul oleh Kerajaan Islam Aceh Darussalam (yang kemudian menyatukan seluruh kerajaan yang ada di wilayah Aceh sebagai mana yang dikenal sekarang) pada akhir abad ke 15 dan permulaan abad ke 16.
Proses ini telah menjadikan Aceh sebagai suatu wilayah Islam yang kemudian lebih dikenal sebagai negeri “Seuramoe Meukah” (Serambi Mekkah). Dalam konteks inilah kemudian Aceh menjadi melekat dengan Islam dan Islam melekat dengan Aceh.
Islam kemudian menjadi suatu identitas yang melekat pada Aceh dan masyarakatnya. Karena proses islamisasi yang telah menyejarah itulah menurut Dhakidae , Islam telah menjadi identitas sosial bagi orang Aceh.
Hal itu terbentuk lewat perjalanan sejarah yang panjang yang menurut Dhofier sebagaimana telah disebut di atas, Islam sudah mulai ada di wilayah Aceh sejak abad pertama Hijriah, yang kemudian terus diperkuat sejak zaman kerajaan Islam Peureulak disusul oleh zaman kerajaan Islam Pase dan zaman kerajaan Aceh Darussalam.
Karenanya, orang Aceh sangat bangga bahwa melalui mereka dan daerah merekalah agama Islam masuk ke Asia Tenggara. Kebanggaan itu bertambah lagi dengan melekatnya julukan Aceh sebagai “Seuramoe Meukah”.
Julukan itu tidak saja karena kedalaman nilai Islam terhujam dalam kehidupan Aceh, namun karena ia juga merupakan sebuah kawasan di mana setiap orang dari Nusantara yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah terlebih dahulu mampir di Aceh untuk memperdalam ilmu agama, begitu juga saat mereka kembali.
Bahkan menurut Melalatoa5 tranformasi nilai-nilai Islam melalui proses sosialisasi, enkulturasi dan pendidikan (formal dan non formal) itu sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan di Aceh.
Sehingga lewat perjalanan dan pengalaman sejarah yang telah berjalan berabadabad lamanya itulah nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam terinternalisasi (diresapi) ke dalam diri anggota masyarakat dan terobyektivasi (tercermin) dalam berbagai sistem berfikir dan aspek kehidupan, baik dalam perilaku, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, seni, teknologi tradisional.
Misalnya dalam hal sistem ekonomi. Di masa lalu seorang pedagang (muge) mengambil hasil pertanian dari petani produsen tanpa transaksi pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran itu baru dilakukan dalam waktu yang relatif lama setelah dagangannya laku.
Transaksi antara broker dan petani itu hanyalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan itu timbul karena mereka yakin, antara sesama muslim tidak akan ada yang berbohong atau menipu. Karena itulah Melalatoa secara umum berpandangan bahwa orang Aceh dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat, bahkan terkesan fanatik.
Demikian juga dalam kehidupan sosial politik pengaruh tradisi Islam juga kental terlihat misalnya dalam mata uang emas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh tertera ungkapan al-sultan al-‘adil (raja yang adil).
Konsep ‘adil yang tertulis dalam kepingan mata uang emas itu dipahami sebagai bentuk aktualisasi Firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran. Tradisi ungkapan al-sultan al-‘adil yang dipopulerkan oleh Kerajaan Samudra Pasai ini bahkan kemudian telah mempengaruhi mata uang Kerajaan-kerajaan Islam di di Tanah Melayu seperti Melaka, Johor, Trengganu, Keudah, Brunai Darussalam.
Apa yang menyebabkan sehingga raja-raja di Pasai yang kemudian diteruskan di Aceh dan raja-raja Melayu lainnya mencantumkan ungkapan al-sultan al’adil pada mata uang mereka? Sejarawan Ibrahim Alfian mengatakan bahwa raja-raja itu berupaya memerintah sesuai dengan kedudukan mereka sebagai raja muslim yang mengikuti perintah Allah.
Hal ini sambung Alfian adalah sesuai sebagaimana tertera dalam Kitab Tajussalatin (Mahkota Segala Raja) karangan Bukhari al-Jauhari yang ditulis di Istana Aceh Darussalam pada 1603.
Dalam kitabnya Jauhari mengutip Surat an-Nahl ayat 90 yang artinya “Bahwa Allah Ta’ala memerintahkan kamu akan berbuat adil dan ihsan”. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan menjadi pegangan bagi rajaraja Islam Mataram dengan judul Serat Tajussalatin.
Dalam kitab Tazkiratur Rakidin Syekh Abbas ibnu Muhammad atau lebih dikenal denga sebutan Teungku Syik Kutakareung menyebutkan: “Adat ban adat hukum ban hukum, adat ngon hukum sama kembar; tatkala mufakat adat ngon hukum, nanggroe seunang hana goga” (“Adat menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum (syara’) sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum, negeri senang tiada huru-hara”).
Yang dipahami sebagai adat dan hukum di sini adalah adat sebagai wilayah politik dan pemimpinnya adalah raja sebagai pimpinan politik. Sedangkan hukum adalah hukum syara’ dan pemimpinnya adalah para alim ulama. Sehingga ungkapan “hana bak gop na bak geutanyoe, saboh nanggroe dua droe raja” memiliki mafhumnya di sini.
Namun satu hal yang perlu diingat dari uraian di atas bahwa aspek syariat Islam sebagai pengejawantahan dari pesan suci Islam adalah nilai keadilan yang kelihatan lebih menonjol dalam sejarah perjalan Islam di Aceh.
Dimensi keadilan ini terutama penegakannya lebih dibebankan pada pemerintah sebagai pemimpin politik dalam penyelenggaraan negara sebagaimana terlihat dalam ungkapan al-sultan al-‘adil dalam mata uang mereka.
Pemerintah di sini dipahami baru wajib diikuti manakala perintahnya itu bersatu dengan agama sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam ayat-ayatNya, Al-Quran Surat al-‘Araf ayat 3 menegaskan.
Sedangkan ulama sebagai pemimpin agama lebih kepada kewajiban untuk menjaga agama, baik agama dalam pengertian ajarannya maupun agama dalam pengertian pengejawantahannya, sehingga para ulama yang disebut sebagai pemegang hukum batin atau nilai-nilai hukum Islam ini juga wajib diikuti perintahnya dan siapa yang tidak patuh akan mendapat bala (mala petaka).
Dalam pengertian yang luas inilah Siegel menyebut Orang Aceh sebagai bangsa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari “Tali Tuhannya”. Kembaran kepemimpinan politik dan agama ini masih dapat kita temui dalam unit teritorial terkecil di Aceh yakni gampong.
Di mana di setiap gampong di Aceh selalu ada seorang keuchiek sebagai pemimpin politik (adat) dalam satu kampung dan teungku imum sebagai pemimpin agama.
B. Perspektif dan Metode Pembahasan
Perspektif dan metode pembahasan tulisan ini dielaborasi dalam bentuk diskusi deduktif – induktif sehingga kemungkinan pengulangan dari setiap uraian yang dibahas tidak dapat dihindari demi mengalirnya proses dialog ini.
Diskusi ini terutama didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang berbicara tentang empat perang yang pernah terjadi di Aceh yang di dalamnya telah berkelindan identitas keacehan yang paling azasi yaitu Islam. Data-data sosial dalam konteks kekinian yang telah diamati juga ditampilkan untuk menunjukkan gejala kontinuitas historis pembahasan.
Islam dan proses islamisasi dipahami tidak saja telah membentuk atau mensetting kesadaran identitas keacehan secara lebih luas tetapi juga dipandang sebagai aspek sosio-historis yang telah membentuk cara pandang diri, cara memahami diri dan cara mengenal diri sebagai Orang Aceh.
Pembahasan tentang empat perang Aceh yang didiskusikan ini pun dipandang didasarkan pada kesadaran identitas dan pandangan dunia sebagai Orang Aceh semacam ini.
Wajah Islam sebagaimana akan ditunjukkan dalam pembahasan nanti tidak saja selalu menjadi roh yang selalu menyelimuti setiap periode perang Aceh tetapi sekaligus juga menjadi energi utama dan tujuan utama dalam setiap periode perang Aceh.
C. Perang Aceh Dengan Belanda
Keutuhan sosial politik Aceh yang sudah dibentuk sejak 1520 akhirnya bertemu dengan Ultimatum Perang Kerajaan Belanda terhadap Kerajaan Aceh Darussalam pada 26 Maret 1873 yang disambut dengan perlawanan Aceh13 dan perang yang baru bisa diatasi Belanda untuk sebagian wilayah Aceh tertentu pada tahun 190414.
Ultimatum Perang ini menunjukkan bukti bahwa sampai saat itu Kerajaan Belanda tetap mengakui kalau Kerajaan Aceh Darussalam itu adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh yang terpisah dari wilayah-wilayah jajahan lainnya yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Belanda sebelumnya.
Pengakuan itu pun bukan tak berdasar mengingat hubungan diplomatik dua negara sebagaimana telah disebutkan di atas, telah terbina antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Oranje sejak Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589-1604) mengirim seberkas surat kepada Prins Mauris (pendiri Dinasti Oranje) untuk memberi pengakuan kemerdekaan kepada Belanda dalam perang kemerdekaannya melawan Spanyol.
Demikian juga dengan hubungan diplomatik dan perdagangan yang telah terjalin antara dua negara sejak yang telah dimulai sejak abad ke 16. Namun 300 tahun kemudian anak cucu Alauddin Riayat Syah ini dipencundangi oleh anak cucu pendiri Dinasti Oranje Prins Mauris.
Dengan semangat kapitalisme beringas dalam wujud kolonialismeimperialisme kemudian Belanda telah membuat ujung sejarah AcehBelanda berada dalam pusaran perang 70 tahun yang pada gilirannya telah menghancur leburkan Kerajaan Aceh dan Aceh dijadikan sebagai tanah jajahan Belanda. Sungguh suatu ironi peradaban. Bagi orang Melayu peristiwa semacam diibaratkan bagai “air susu dibalas air tuba”.
Hari itu Rabu 26 Maret 1873, bertepatan dengan 26 hari bulan Muharram 1290 H. Dari geladak kapal komando Citadel van Antwerpwn – yang berlabuh di antara pulau Sabang dengan daratan Aceh – Kerajaan Belanda memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh .
Sejak saat itu Kerajaan Aceh Darussalam dan rakyatnya berperang mati-matian melawan agresi Belanda. Padahal sebelumnya, Acehlah negara timur pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol.
Peperangan Aceh dengan Belanda itu kemudian telah membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Kehancuran terutama sangat dirasakan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Belanda dapat menduduki Dalam pada tanggal 22 Januari 1874 kemudian Sultan dan pengikutnya mengungsi ke Lueng Bata di Banda Aceh dan akhirnya kemudian bermarkas di Keumala Pidie sampai kemudian ditawannya Sultan terakhir Kerajaan Aceh Darussalam Alaiddin Muhammad Daud Syah pada 10 Januari tahun 1903.
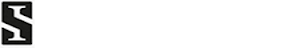


Posting Komentar untuk "POLITIK IDENTITAS ISLAM DAN EMPAT PERANG ACEH"