Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu,
pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan
dibanding dengan yang lain.
Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi
yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum-pemilihan
umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem
pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.
Zaman Demokrasi Parlementer (1945−1959)
Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober
1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan dua
kali, yaitu satu kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September, dan
satu kali untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember.
Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu sistem
itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya
sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin
negara.
Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana khidmat, karena merupakan pemilihan umum pertama dalam suasana kemerdekaan.
Pemilihan
umum berlangsung sangat demokratis; tidak ada pembatasan partai-partai,
dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partaipartai sekalipun kampanye berjalan seru, terutama antara Masyumi dan PNI.
Pun pula, administrasi teknis berjalan lancar dan jujur.
Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, dengan
jumlah total 257 kursi (lihat Bagan di bawah). Sekalipun jumlah partai bertambah dibanding dengan jumlah partai sebelum pemilihan umum, namum ada
4 partai yang perolehan suaranya sangat menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU,
dan PKI.
Bersama-sama mereka meraih 77% dari kursi di DPR. Sebaliknya, beberapa partai yang tadinya memainkan peranan penting dalam percaturan
politik ternyata hanya memperoleh beberapa kursi.
Namun stabilitas politik yang sangat diharapkan dari pemilihan umum
tidak terwujud.
Kabinet Ali (I dan II) yang memerintah selama dua tahun
dan yang terdiri atas koalisi Tiga Besar: Masyumi, PNI, dan NU, ternyata tidak
kompak dalam menghadapi beberapa persoalan, terutama yang terkait
dengan Konsepsi Presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957.
Karena beberapa partai koalisi tidak menyetujuinya, akhirnya beberapa
menteri, antara lain dari Masyumi, keluar dari kabinet. Dengan pembubaran
Konstituante oleh Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir
dan kemudian mulai zaman Demokrasi Terpimpin.
Zaman Demokrasi Terpimpin (1959−1965)
Sesudah mencabut Maklumat Pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai
menjadi 10.
Kesepuluh partai ini—PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti—kemudian ikut
dalam pemilihan umum 1971 di masa Orde Baru. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak diadakan pemilihan umum.
Zaman Demokrasi Pancasila (1965−1998)
Sesudah runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil.
Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya Musyawarah Nasional III Persahi 1966, dan Simposium Hak Asasi Manusia,
Juni 1967. Diskusi yang paling penting diadakan di SESKOAD, Bandung pada
tahun 1966.
Pada Seminar Angkatan Darat II ini dibicarakan langkah-langkah
yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik, karena ulah mereka dianggap telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik.
Salah satu caranya ialah melalui sistem pemilihan umum (lihat Bab Partai
Politik).
Pada saat itu diperbincangkan tidak hanya sistem proporsional yang
sudah lama dikenal, tetapi juga sistem distrik, yang di Indonesia masih sama
sekali baru. Seminar berpendapat bahwa sistem distrik dapat mengurangi
jumlah partai politik secara alamiah, tanpa paksaan.
Diharapkan partai-partai
kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerja sama dalam usaha meraih
kursi dalam suatu distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan
membawa stabilitas politik, dan pemerintah akan lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, terutama di bidang ekonomi.
Namun keputusan seminar yang kemudian dituangkan dalam suatu RUU ditolak oleh
partai-partai dalam DPR pada tahun 1967. Dikhawatirkan bahwa sistem distrik akan merugikan eksistensi partai-partai politik, dan juga karena ada usul
untuk memberikan jatah kursi di DPR kepada ABRI.
Dengan ditolaknya sistem distrik maka semua pemilihan umum berikutnya dilaksanakan dengan
memakai sistem proporsional.
Sebagai akibatnya, sistem proporsional tahun 1995 tetap menjadi pilihan namun dengan beberapa modiikasi.
 |
| Undian Nomor Partai Politik pada Pemilu 1971 |
Pertama, setiap daerah tingkat II
(kabupaten/kotamadya) dijamin mendapat satu kursi di DPR. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan jumlah anggota DPR dari Jawa dan luar Jawa, karena jumlah pemilih di Jawa jauh lebih banyak dari jumlah pemilih di
luar Jawa.
Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 di antaranya diangkat, yaitu 75
anggota diangkat dari ABRI dan 25 lainnya dari non-ABRI. Yang non-ABRI ini
diangkat dari Utusan Golongan dan Daerah. Berdasarkan kompromi antara
partai-partai dan pemerintah, yang dinamakan Konsensus Nasional, maka
pemilihan umum 1971 diselenggarakan dengan 10 partai politik.
Untuk perimbangan jumlah anggota parlemen dan penduduk dibuat perbandingan
1:400.000.
Karena gagal menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan
umum, Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian.
Tindakan pertama ialah mengadakan fusi di
antara partai-partai. Di hadapan partai-partai, Presiden Soeharto pada tahun
1973 mengemukakan saran agar mereka mengelompokkan diri dalam tiga
golongan yaitu Golongan Spiritual, Golongan Nasionalis, dan Golongan Karya, sehingga hanya tinggal tiga partai politik yaitu Golkar, PPP, dan PDI.
Maka mulai tahun 1977 pemilihan umum diselenggarakan dengan
menyertakan tiga partai. Golkar selalu menang secara meyakinkan dan meraih kedudukan mayoritas mutlak.
Tindakan lain yang menguntungkan Golkar dimuat dalam UU No. 3 Tahun 1975, bahwa kepengurusan partai-partai
terbatas pada ibu kota tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. Ketentuan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah massa mengambang (loating mass).
Dalam praktik peraturan itu menguntungkan Golkar karena dua partai hanya
dibenarkan aktif sampai ke tingkat kabupaten atau Dati II, padahal Golkar
bebas untuk bergerak sampai ke tingkat desa, di mana ia bekerja sama dengan aparat pemerintah.
Perbedaan itu dimungkinkan karena pada waktu
itu Golkar tidak dianggap sebagai partai. Selain dari itu, dalam pelaksanaan
sehari-hari aparat pemerintah mengadakan intervensi berlebih-lebihan, ter utama di daerah-daerah terpencil, dalam usaha mencapai target yang telah
ditentukan.
Jika meninjau perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia,
dapat ditarik berbagai kesimpulan. Pertama, keputusan untuk tetap menggunakan sistem proporsional pada tahun 1967 adalah keputusan yang tepat karena tidak ada distorsi (distortion efect) atau kesenjangan antara perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam DPR.
Dengan demikian
setiap suara dihitung dan si pemilih merasa puas bahwa suaranya ada maknanya (betapa kecil pun) dalam proses pemilihan pemimpinnya.
Kedua, ketentuan di dalam UUD 1945 bahwa DPR dan presiden tidak dapat saling
menjatuhkan merupakan keuntungan, karena tidak ada lagi gejala sering
terjadinya pergantian kabinet seperti di zaman Demokrasi Parlementer.
Eksekutif mempunyai masa jabatan tetap, yaitu lima tahun. Ketiga, tidak ada
lagi fragmentasi partai karena yang dibenarkan eksistensinya hanya tiga
partai saja. Usaha mendirikan partai baru tidak bermanfaat lagi dan tidak
diperbolehkan.
Dengan demikian sejumlah kelemahan dari sistem proporsional telah teratasi.
Namun beberapa kelemahan masih melekat pada sistem politik ini. Pertama, masih kurang dekatnya hubungan antara wakil pemerintah dan konstituennya tetap ada.
Kedua, dengan dibatasinya jumlah partai menjadi tiga
telah terjadi penyempitan dalam kesempatan untuk memilih menurut selera
masing-masing sehingga dapat dipertanyakan apakah pilihan si pemilih benar-benar mencerminkan kecenderungannya, atau ada pertimbangan lain yang menjadi pedomannya.
Sekalipun demikian harus diakui bahwa angka
voter turnout 90% ke atas antara jumlah partisipasi Demokrasi Parlementer
dan di zaman Reformasi (keduanya tanpa paksaan) dan jumlah partisipan di
masa Orde Baru (dengan unsur mobilisasi) tidak memperlihatkan perbedaan
signiikan.
Akhirnya, jika sebelumnya dikemukakan bahwa sistem distrik kurang
baik untuk Indonesia, maka Bagan di bawah ini menunjukkan sebagai suatu
contoh yang konkret bahwa dalam beberapa kasus partai kecil seperti PPP
dan PDI sangat diuntungkan dengan sistem proporsional, sedangkan Golkar
(partai besar) bisa saja dirugikan oleh sistem proporsional itu.
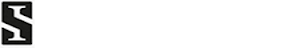


Posting Komentar untuk "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia"